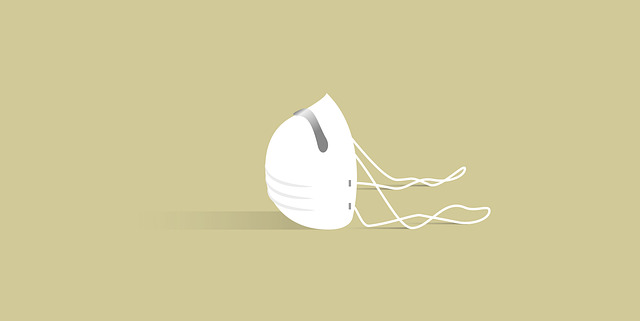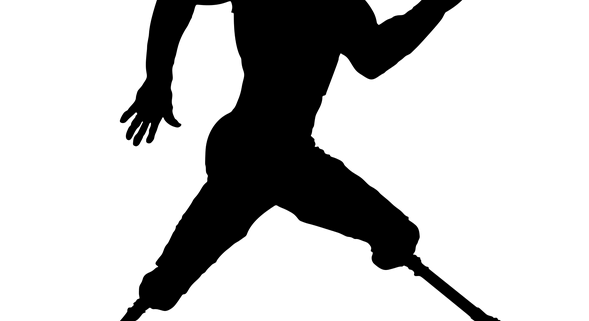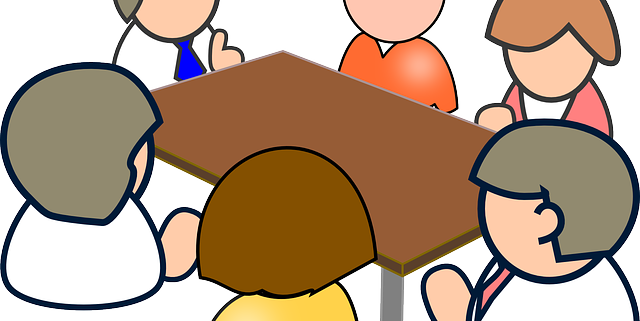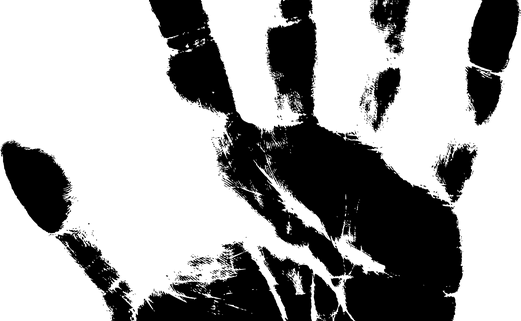Penulis: M. Syafi’ie, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Departemen Hukum Tata Negara
Suatu saat penulis bertanya kepada seorang guru, dimana posisi hukum dalam agama Islam? Beliau menjawab bahwa hukum merupakan bagian dari Islam. Ajaran hukum lebih kecil dibanding dengan ajaran Islam yang luas antara lain terkait aqidah, akhlaq, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan hukum umumnya dikaitkan dengan ibadah dan muamalah yang menjadi domain fiqh.
Muhammad Adnan mengatakan, agama diterjemahkan dari bahasa Arab Ad-Din, Asy-syari’ah at-Thoriqoh, dan Millah yang diartikan sebagai peraturan dari Allah untuk manusia berakal, untuk mencari keyakinan, mencapai jalan bahagia lahir bathin, dunia akhirat, bersandar kepada wahyu-wahyu ilahi yang terhimpun dalam Kitab Suci yang diterima oleh Nabi Muhammad.
Islam menurut A. Gaffar Ismail ialah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang berisi kelengkapan dari pelajaran-pelejaran yang meliputi : (a) kepercayaan; (b) seremoni-peribadahan; (c) tata tertib kehidupan pribadi; (d) tata tertib pergaulan hidup; (e) peraturan-peraturan Tuhan; (f) bangunan budi pekerti yang utama, dan menjelaskan rahasia kehidupan yang akhirat.
Hukum sendiri berasal dari bahasa arab hakama-yahkumu-hukman (masdar) yang dalam Kamus Arab-Indonesia Mahmud Junus diartikan dengan menghukum dan memerintah. Hukum juga diartikan dengan memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum dapat dimaknai dengan norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.
Dalam ushul fiqh, hukum syar’i diartikan dengan khitab (kalam) Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa iqtidha’ (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan), takhyir (memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau wadh’i (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang/mani’)
Maksud dari khitabullah ialah semua bentuk dalil-dalil hukum yang bersumber dari Qur’an, Sunnah serta ijma’ dan qiyas. Menurut Abdul Wahab Khalaf, yang dimaksud dengan dengan dalil hanya Qur’an dan Sunnah, sedangkan ijma’ dan qiyas merupakan upaya ijtihadi untuk menyingkap hukum dari Qur’an dan Sunnah. Kita tahu, ada banyak metode ijtihad untuk menggali hukum syar’i, antara lain : qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, al-‘adah, dan fathu ad-dzari’ah dan sadd al-dzari’ah.
Hukum Islam secara umum dapat dibagi menjadi dua, pertama, hukum taklifi yang terdiri dari al-wujub (wajib), an-nadbu (sunnat), al-ibahah (mubah), al-karoheh (makruh), dan al-haromah (haram). Contohnya, wajib puasa bulan Romadhan, haramnya minum khamar, mubahnya makan minum, serta makruhnya merokok. Kedua, hukum wadh’iy yang didalamnya ada sebab, syarat, mani’, sah-batal, rukhsoh-‘azimah. Contohnya, waktu matahari tergelincir di tengah hari menjadi sebab wajibnya seorang mukallaf menunaikan sholat dzuhur, wudhu’ menjadi syarat sahnya sholat, haid menjadi penghalang (mani’) seorang perempuan melakukan kewajiban sholat atau puasa.
Pemikiran di atas memperlihatkan bahwa ada perbedaan antara Islam sebagai agama, dan hukum sebagai bagian dari agama Islam. Perbedaan tersebut sangat kecil, karena itu ada tiga konsep yang wajib diketahui dan dipahami oleh seorang muslim, yaitu syari’ah, fiqh, dan qonun. Mengetahui ketiganya akan mengantarkan kepada seorang muslim untuk mengerti mana wilayah yang tidak mungkin berubah dan tunggal, serta mana wilayah yang bisa berubah dan berbeda-beda tafsirnya.
Menurut Hasbi As-Shiddieqy, syariat berarti jalan tempat keluarnya sumber mata air atau jalan yang dilalui air terjun yang diasosiakan oleh orang Arab sebagai at-thhariqah al-mustaqimah. Secara terminologi, syariat berarti tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti (Qs. Al-Jasiyah : 18). Fiqh menurut Fathurrman Djamil ialah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Allah. Fiqh memiliki keterkaitan dengan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang bersumber pada dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan qonun biasa diartikan dengan Undang-Undang. Ulama’ salaf mendefinisikannya sebagai kaidah-kaidah yang bersifat kully (menyeluruh) yang didalamnya tercakup hukum-hukum juz’iyyah (bagian-bagiannya). Qonun umumnya dibuat oleh pemerintah yang berkuasa.
Syari’ah, fiqh dan qonun berbeda. Ajaran syari’at tedapat dalam Qur’an dan hadist yang tidak mungkin berubah teksnya, bersifat fundamental, abadi karena merupakan ketetapan Allah dan Nabi Muhammad, tunggal yang meperlihatkan konsep kesatuan Islam. Sedangkan fiqh dan qonun merupakan produk pemahaman manusia yang menggali hukum dalam Qur’an dan hadist, bersifat instrumental, mengalami perubahan sesuai waktu, zaman serta keadaan. Realitasnya seperti yang kita ketahui saat ini, dimana produk hukum fiqh dan qonun cenderung berbeda-beda sesuai madzhab yang sangat beragam. Kita bisa lihat perbedaan-perbedaan tersebut dalam kitab-kitab fiqh perbandingan.
Uraian di atas memperlihatkan kepada kita bahwa saat kita memeluk agama Islam kita satu, syariatnya tunggal yaitu Al-Qur’an dan Hadist, tetapi saat bersamaan kita umumnya mengikuti ‘hukum’ atau ‘qonun’ madzhab tertentu, disitulah beberapa praktik keagamaan umat Islam berbeda-beda. Dalam konteks ini, biar tidak kagetan dan apalagi sampai mengkafirkan, umat Islam dituntut untuk belajar ilmu-llmu yang menjadi basis hukum dalam Islam seperti ilmu Ushul Fiqh, Qowaidul Fiqh, Perbadingan Madzhab, Maqosid Syari’ah, Ulumul Qur’an, Ulumul Hadist, Ulumul al- Tafsir, dan Ilmu Mantiq (Logika).
Tulisan ini telah dimuat dalam UII News edisi Maret 2021.