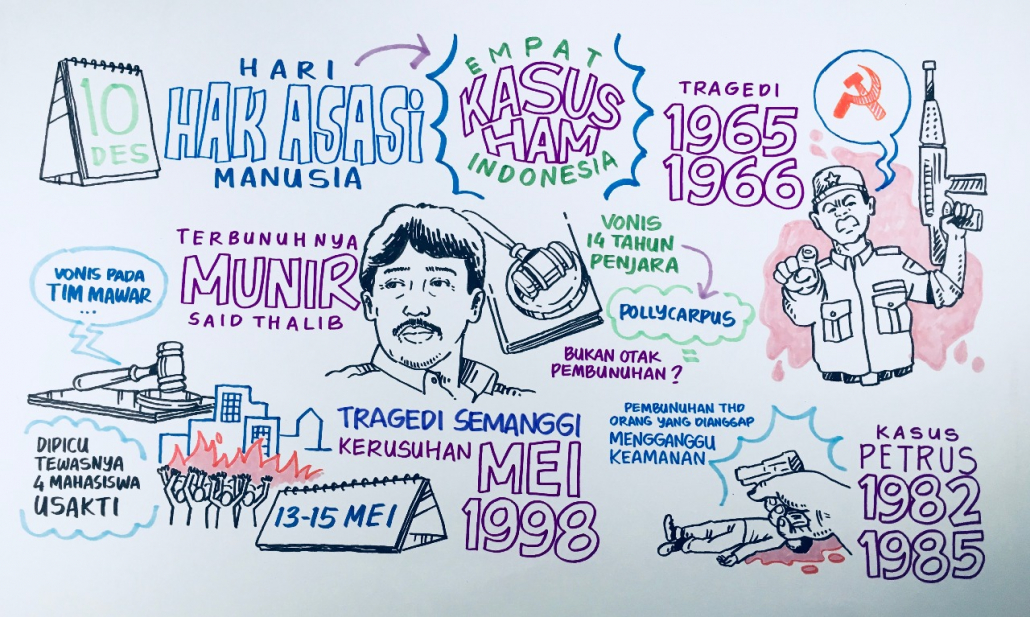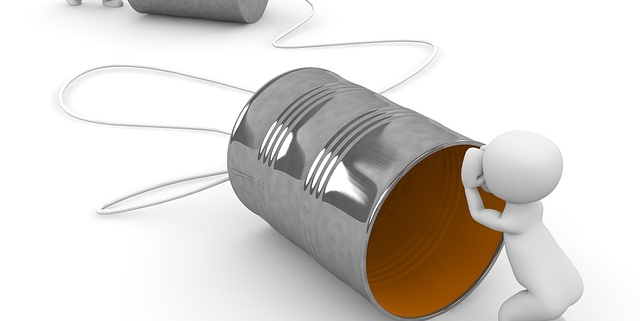Author: Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M
Lecturer in Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Departement of Constitutional Law
Ada dua poin besar dalam draft revisi UU MK yang menuai kritik dan penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat. Pertama, menambah syarat minimal usia untuk menjadi hakim konstitusi dari 47 menjadi 60 tahun. Kedua, mengubah ketentuan aturan masa jabatan hakim konstitusi dari model periodesasi ke batas usia maksimum 70 tahun. Dalam lanskap politik dan tehnik legislasi, dua kalusul ini cenderung sangat spekulatif. Belum ada satupun hasil studi yang membenarkan bahwa menambah syarat usia hakim konstitusi bisa memengaruhi kualitas interpretasi terhadap sebuah perkara.
Sungguhpun itu dibentuk sebagai syarat, pengaturan batas minimal usia tak lebih dari sebuah kompromi politik. Dan adakalanya, rasionalisasi pilihan angka itu jatuh secara insidentil. Begitu juga dalam konteks masa jabatan hakim konstitusi. Terlalu dini kiranya jika ada persepsi yang menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan hakim dengan klausul usia maksimum akan menguatkan independensinya dalam mengadili perkara. Sebab independensi jabatan hakim tidak dipengaruhi dengan syarat usia, melainkan pada prinsip meritokrasi yang melekat dalam proses seleksi dan pengangkatan hakim. Tak heran kiranya, jika masyarakat dibuat bingung dengan kebutuhan revisi UU MK. Apa yang menjadi motif di balik dua kalusul itu? Poin perubahan yang sama sekali tidak substantif, bahkan membuka konflik kepentingan antara hakim konstitusi dan pembentuk undang-undang.
Legislasi
Menjadi menarik bila meletakkan konteks ini jauh lebih luas. Di periode kedua pemerintahan Joko Widodo, fungsi legislasi menjadi anasir yang secara signifikan mendapatkan krisis legitimasi sosial. Begitu masifnya penolakan publik dalam fungsi legislasi (Presiden-DPR) tentu tidak bisa hanya dimaknai sebagai bekerjanya kontrol kewargaan dalam negara demokrasi. Melainkan juga harus dilihat sebagai bentuk pentingnya evaluasi kinerja Presiden dan DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi. Berawal dari proses politik yang buruk pada perubahan UU KPK dan juga diikuti dengan perubahan UU Minerba, krisis legitimasi publik kemudian mengerangkai pada pembentukan undang-undang lainnya. Sebut saja RUU Cipta Kerja, sampai dengan yang paling anyar revisi UU MK. Dalam konsepsi hukum dan masyarakat, undang-undang bukan hanya soal legalitas formal melainkan juga legitimasi sosial (Sulistiyowati Irianto:2019). Luc Wintgens: 2012 menuliskan bahwa krisis legitimasi publik terhadap pembentukan undang-undang disebabkan akibat proses legislasi yang buruk baik dari segi prosedur maupun isi dari undang-undang itu sendiri. Rasionalitas publik ditabrak atas dasar kehendak partai, partisipasi publik lemah dan suara rakyat dibajak dengan kelompok-kelompok penekan yang memiliki kepentingan sektoral atas pembentukan sebuah undang-undang.
Independensi
Studi Larkins dalam “judicial independence and democratization” membenarkan bahwa pola intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan salah satunya dilakukan dengan proses politik pembentukan undang-undang yang mengatur lembaga peradilan (Christoper M Larkins:1996). Polanya sederhana. Pemerintah memperdagangkan pengaruh dalam materi muatan pembentukan hukum, agar hakim terjebak pada pusaran konflik kepentingan. Praktik di berbagai negara merefleksikan keadaan yang hampir mirip. Intervensi pemerintah dilakukan dengan proses politik pada revisi undang-undang kekuasaan kehakiman. Hungaria contohnya, pemerintah Orban mengubah aturan dengan menambah jumlah hakim konstitusi dari delapan menjadi lima belas. Kemudian memberikan peran bagi partai penguasa untuk melakukan penunjukan langsung terhadap hakim-hakim yang baru. Demikian juga Polandia. Partai pemenang pemilu menolak calon hakim yang diusulkan oleh partai pendukung pemerintah sebelumnya. Kemudian partai pemenang pemilu mengangkat lima hakim konstitusi yang baru untuk mendelegitimasi calon yang lama. Semua itu dilakukan agar pemerintah dapat memberikan pengaruh terhadap hakim ketika dan akan mengadili perkara yang melibatkan kepentingan pemerintah. Ketika hakim tidak lagi independen, proses peradilan menjadi sangat transaksional.
Kepentingan
Dalam draft revisi UU MK, Pasal 87 huruf c mengatur apabila hakim konstitusi berakhir masa jabatannya di usia 60, maka hakim yang bersangkutan dapat meneruskan jabatannya hingga usia 70 tahun. Tanpa adanya kejelasan dalam ketentuan peralihan, pasal ini bisa mengancam dan mengakibatkan hakim konstitusi terjebak dalam kubangan konflik kepentingan. Artinya akan ada hakim konstitusi yang dirugikan ataupun diuntungkan dengan ketentuan perubahan UU MK. Sebagai contohnya Hakim Saldi Isra. Periodesasi jabatannya habis sebelum usia enam puluh tahun. Berbanding terbalik dengan Hakim Aswanto yang periodesasi jabatannya bisa berhenti di usia enam puluh tahun. Dengan merujuk ketentuan revisi pasal a quo akan ada hakim konstitusi yang mungkin saja bisa menjabat hingga dua puluh tahun lamanya. Bisa dibayangkan ketika revisi UU a quo pada akhirnya diujikan di MK, majelis hakim konstitusi tidak hanya mengadili kepentingan lembaganya, melainkan juga mengadili kepentingan jabatannya sendiri. Oleh karena itu revisi UU MK sebaiknya lebih ditujukan untuk mengoptimalisasi pemenuhan hak konstitusional warga negara. Menelaah kebutuhan kelembagaan MK yang jauh lebih substantif dari pada sekedar mengatur usia jabatan hakim. Bukan sebaliknya, momentum revisi UU MK justru hanya menjadi langkah mundur dalam upaya perlindungan hak konstitusional warga negara.
This article have been published in detikNews, 16 June 2020.