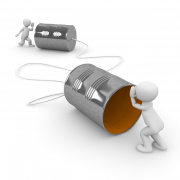Mengembalikan GBHN
Penulis: Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Departemen Hukum Tata Negara
Apakah sudah diperhitungkan rencana amandemen terbatas UUD yang sudah semakin mengkristal pada romantisme GBHN? Adakah studi kelayakan yang telah memberikan preposisi bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional kita bermasalah sehingga tidak relevan lagi untuk digunakan? Seberapa dalam cetak biru yang telah disusun MPR, metode risetnya apa, sehingga GBHN menjadi laik diterapkan kembali sebagai kerangka dasar pembangunan nasional. Sungguhpun sudah dipikirkan secara matang, bagaimana dengan proses dan mekanisme perubahannya?
Sejumlah pertanyaan di atas, mengirimkan pesan bahwan wacana amademen terbatas perlu dikonstruksikan secara komprehensif. Dibangun melalui konsep yang kuat, serta memperhatikan sejumlah ekses yang kemungkinan dapat ditimbulkan. Jika tidak, proyek besar ini bisa kebablasan dan justru menambah sengkarut problem ketatanegaraan.
Dalam ketentuan hukum positif saat ini, beberapa perangkat regulasi pada dasarnya telah mengakomodir arah pembangunan dan haluan bernegara. Misalnya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN, UU No 25 Tahun 2004) dan Rancana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP UU No 17 Tahun 2007). Bahkan secara lebih detail, arah pembangunan juga diderivasikan lagi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang meliputi pembangunan nasional, bidang, dan wilayah.
Jika hendak memahami arah politik hukum pembangunan nasional pascatransisi politik, sebenarnya tidak terlihat garis demarkasi yang tajam antara politik pembangunan era orde baru dengan politik pembangunan saat ini. Melalui perangkat SPPN, RPJPN, dan RPJMN, pembangunan nasional juga dapat dialkukan secara terukur dan sistematis. Artinya, secara materiil hampir tidak ada pembedaan cara kerja pada model pembangunan bergaya GBHN dengan model SPPN dan RPJP. Setidaknya, titik pembedaan itu hanya pada aspek formalnya saja.
Jika arag pembangunan nasional di era orde baru diterapkan MPR, maka arah pembagunan nasional saat ini ditetapkan Presiden dan DPR melalui kerangka legislasi nasional. Pilihan politik hukum demikian tidak lahir tanpa basis rasionalitas politik yang kuat. Laiknya sebuah silogisme hukum, ada beberapa alasan mengapa GBHN tidak lagi relevan diterapkan pascatransisi politik.
Pertama, soal kesepakatan dasar perubahan UUD di era transisi. Saat itu, semua partai politik sepakat bahwa agenda perubahan UUD dilandaskan pada semangat memperkuat sistem presidensiil (Valina Singka:2008). Dengan mempertahankan model pembangunan melalui GBHN, sistem pemerintahan akan jauh berayun pada gaya parlementer. Seluruh pertanggungjawaban politik akan diserakan ke MPR. Tidak menutup kemungkinan MPR akan kembali menjadi pemegang kendali atas kuasa rakyat.
Kedua, masa jabatan presiden yang limitatif tidak akan kompatibel dengan model pembagunan GBHN. Sebagai sebuah produk politik, upaya perubahan terhadap materi muatan GBHN menjadi sangat mungkin terjadi. Perkembangan koalisi kepartaian sangat dinamis, menyebabkan GBHN menjadi sangat sulit diterima dan diterapkan pada pemerintahan berikutnya.
Ketiga, dengan menerapkan model pembangunan berbasis GBHN, ada berbagai macam implikasi yang ditimbulkan terhadap sistem hukum nasional. Mulai dari posisi tawar GBHN terhadap hierarki perundang-undnagan sampai dengan model pengujian norma hukum yang bisa saja bertentangan dengan GBHN. Membaca sejumlah tantangan di atas, maka keinginan melakukan amandemen terbatas bisa saja melebar menjadi isu yang tak terbatas.
Terlepas dari rentetan panjang yang mungkin biosa ditimbulkan, tidak kalah penting ialah mengawal bagaimana proses pembuatan itu akan dilakukan. Sebuah konstitusi yang demokratis tidak akan mungkin dihasilkan melalui proses politik yang kolutif. Seperti disematkan Bianc, bahwa proses itu akan menentukan hasil perubahan konstitusi. (Bonime Blanc: 1987). Perlu diingat setelah perubahan UUD, MPR merupakan lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Ia tak lagi sebatas lembaga yang menetapkan, tetapi juga menjadi bagian dalam proses perubahan UUD. Imbasnya peranan partai politik menjadi sangat dominan.
Dengan peta politik demikian, MPR bisa saja terdistorso dengan konflik kepentingan. Sebab, materi muatan amandemen justru menyangkut kepentingan kelembagaannya sendiri. Ada baiknya proyek besar untuk MPR itu perlu dipertimbangkan kembali. Biar bagaimanapun, konstitusi merupakan norma fundamental. Ia hidup dan berkembang dalam praktik berbangsa dan bernegara. Bukan komoditas kepentingan golongan yang bersifat sektoral.