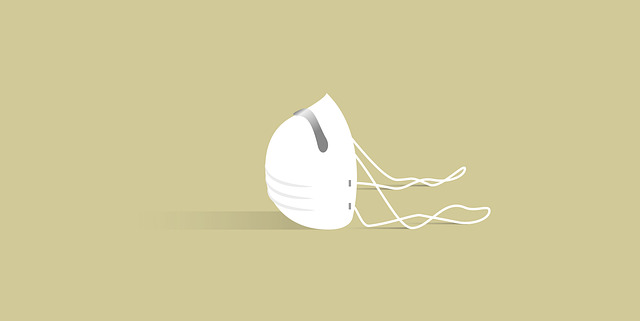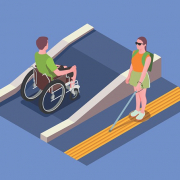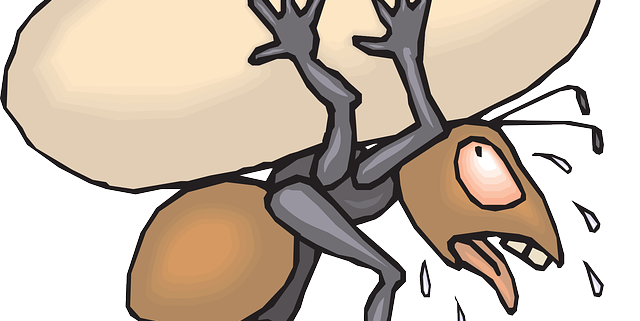Penulis: M. Syafi’ie, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Departemen Hukum Tata Negara
Penularan Covid-19 terus meningkat. Publik seperti dihadapkan pada ketidakpastian langkah-langkah pemenuhan hak atas kesehatan. Bahkan, pemerintah mulai meragukan kebijakannya sendiri. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menggantikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai tidak efektif menghentikan laju penularan. Situasi ini bermakna bahwa penanganan Covid-19 di Indonesia sampai saat ini belum berhasil.
Sejauh ini, sudah banyak peraturan dan kebijakan terkait Covid-19, antara lain : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Pencepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.
Selain itu, ada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Permenkes No. 9 tahun 2020 yang secara spesifik mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keputusan Menteri kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan yang diantaranya mengatur kebijakan tentang mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker, dan yang terakhir Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019.
Melihat ketentuan di atas, sudah banyak peraturan dan kebijakan yang telah dibuat. Pertanyaannya, mengapa kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat? Pertanyaan ini bisa dijawab bahwa substansi dan struktur hukum tersebut belum berjalan efektif dan belum mampu menjadi sarana pengubah perilaku masyarakat.
Hukum Pengubah Perilaku
Roscoe Pound, tokoh aliran hukum Sociological Jurisprudence mengatakan bahwa hukum semestinya dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Hukum mesti dipahami sebagai suatu proses (law in action) yang hukum tersebut sama sekali berbeda dengan hukum yang tertulis (law in books). Peraturan dan kebijakan tentang Covid-19 semestinya dilihat dalam konteks ini, bahwa aturan tersebut bukanlah norma-norma tertulis saja, tetapi norma yang harus dihidupkan dan dilekatkan dengan lembaga kemasyarakatan.
Roscoe Pound mengatakan, hukum berkaitan dengan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Kepentingan tersebut ada 3 (tiga), pertama, public interest yang meliputi kepentingan negara yang tugasnya memelihara hakekat negara dan menjaga kepentingan sosial. Kedua, kepentingan perorangan yang meliputi kepentingan pribadi dan kepentingan dalam rumah tangga. Ketiga, kepentingan sosial yang terkait dengan keamanan umum, moral umum, kemajuan sosial dan kehidupan individu.
Kepentingan penanganan Covid-19 merujuk pemikiran Pound sudah sangat memenuhi dalam dimensi kepentingan pribadi, sosial dan negara. Persoalannya terletak bagaimana peraturan yang ada dapat menggerakkan lembaga pemasyarakatan untuk mendorong tujuan-tujuan sosial dan perorangan di bidang kesehatan. Jika konsep ini dilakukan, peraturan dan kebijakan Covid-19 tentu akan menjadi alat rekayasa masyarakat (law as a tool of social engineering)
Persoalannya, perilaku masyarakat saat ini tidak banyak berubah untuk mentaati protokol kesehatan. Penggunaan masker, menjaga jarak, dan aktifitas cuci tangan tidak ditaati. Kegiatan bergerombol dan mobilitas masyarakat masih sangat tinggi. Situasi ini bermakna bahwa aturan dan kebijakan belum berjalan dengan semestinya. Aparat yang memiliki kewenangan penanganan Covid-19 belum mampu membangun kesadaran yang utuh akan makna penting protokol kesehatan.
Soerjono Soekanto berpendapat, apabila hukum tidak berjalan dengan semesetinya maka harus dicek faktor-faktor yang menjadi penghambatnya, biasanya antara lain terjadi karena faktor pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam masyarakat. Faktor penghambat harus diidentifikasi.
Salah satu yang biasa jadi faktor penghambat menurut Soerjono Soekanto ialah komunikasi hukum. Hukum yang diharapkan dapat mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat harus disebarkan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat. Komunikasi hukum harus dapat dilakukan secara formal dan informal. Cara ini merupakan bagian yang dinamakan difusi, yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan tertentu di dalam kehidupan masyarakat.
Pada pokoknya ketaatan hukum sangat dipengaruhi oleh dua faktor, pertama, tujuan hukum harus identik dengan tujuan/aspirasi anggota-anggota masyarakat. Makna lainnya, taatnya masyarakat pada hukum karena terdapatnya perasaan keadilan dan kebenaran dalam hukum. Kedua, adanya kekuasaan yang imperatif melekat pada hukum dengan sanksi apabila ada orang yang melanggarnya.
Berangkat dari pemikiran di atas, terbayang dalam pikiran kita bahwa ada banyak faktor hukum dan dimensi sosial politik yang mempengaruhi lemahnya ketaatan hukum masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Sebagian besar masyarakat masih belum menangkap kebenaran protokol kesehatan sebagai sesuatu yang penting, dan pada sisi yang lain penegakan hukum masih sangat lemah.
Tentu masih banyak faktor lain yang bisa diidentifikasi dan ditemukan akar masalahnya. Mengubah perilaku masyarakat tidak mudah, apalagi didalamnya ada dimensi sosial keagamaan. Butuh multi pendekatan untuk menciptakan kesadaran akan makna penting mentaati kebijakan protokol kesehatan. Kegagalan penanganan Covid-19 saat ini lebih pada konteks ini : tidak fokus pada pokok masalah, sentralistik, bahasa kebijakan yang tidak membumi, dan kebijakan yang selalu berubah-ubah sehingga cenderung membingungkan masyarakat bahkan pemerintah sendiri.
Tulisan ini telah dimuat pada Koran Sindo, 10 Februari 2021.