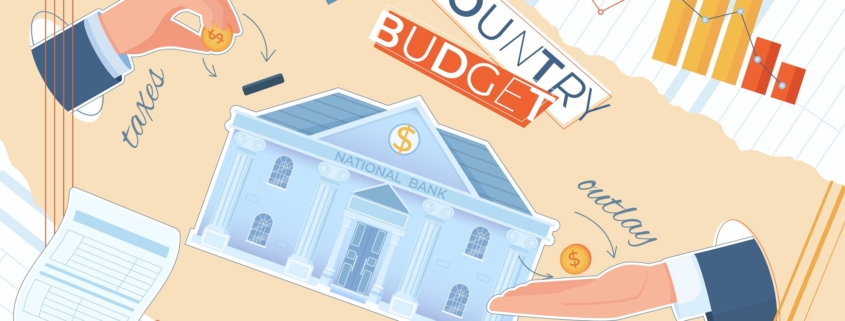Oleh: Gavran Ziksan – 23410654
Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Reguler Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Fenomena migrasi tenaga kerja menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap sosial, ekonomi, dan kebijakan hukum di Indonesia. Ribuan warga negara Indonesia, atau yang dikenal sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), mempertaruhkan nasib di berbagai belahan dunia dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan prospek masa depan yang lebih cerah bagi keluarga mereka di tanah air. Kontribusi ekonomi mereka melalui remitansi tak dapat dipungkiri, menjadi salah satu faktor penting dalam perolehan devisa negara. Namun, di balik narasi keberhasilan dan harapan, tersimpan pula realitas pahit yang kerap menimpa para pekerja ini, yaitu jerat penipuan dan penempatan ilegal yang berujung pada eksploitasi hingga perdagangan orang.
Permasalahan penempatan PMI secara non-prosedural bukanlah isu baru, namun kompleksitas dan dampaknya terus berkembang. Jaringan sindikat yang terorganisir rapi kerap memanfaatkan minimnya informasi, kerentanan ekonomi, dan harapan besar para calon pekerja migran. Dengan iming-iming gaji fantastis dan proses keberangkatan yang mudah tanpa melalui jalur resmi, mereka menjerumuskan PMI ke dalam situasi yang tidak aman dan melanggar hukum tidak hanya mencoreng citra perlindungan tenaga kerja Indonesia di mata internasional, tetapi juga menimbulkan kerugian besar, baik secara material, fisik, maupun psikologis, bagi individu dan keluarga yang terdampak. Banyak dari mereka yang akhirnya bekerja di luar sektor yang dijanjikan, tanpa kontrak yang jelas, bahkan menjadi korban kekerasan dan bentuk perbudakan modern.
Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang terus berkembang. Batam dan wilayah Kepulauan Riau yang dikenal sebagai pintu gerbang Nusantara menuju Asia Tenggara menjadi salah satu titik rawan yang strategis bagi sindikat perdagangan manusia lintas negara. Letak geografis yang dekat dengan Singapura dan Malaysia menjadikan wilayah ini bukan hanya jalur transit, tetapi juga tujuan praktik perdagangan manusia.
Tulisan ini menyoroti sebuah kasus nyata yang berhasil diungkap di Batam pada Mei 2025. Aparat penegak hukum dari Polsek Nongsa dan Sagulung berhasil membongkar praktik penempatan PMI ilegal yang terstruktur. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas pengiriman calon PMI secara non-prosedural di sebuah rumah di Perumahan Azure Gardenia, Batam. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang perempuan berinisial SNI yang diduga menjadi pelaku utama. Di lokasi, petugas menemukan tiga calon PMI perempuan, masing-masing berinisial HH, UF, dan S, yang telah dipersiapkan untuk diberangkatkan ke luar negeri tanpa prosedur resmi. Ketiganya berasal dari Jakarta, Ciamis, dan Pringsewu. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk tiga paspor atas nama korban dan tiket pesawat. Kapolsek Sagulung, Iptu Rohandi Parlindungan Tambunan, menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik penempatan PMI ilegal. Pelaku dijerat dengan Pasal 81 Jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Indonesia telah mengadopsi kerangka hukum yang kuat untuk melindungi warganya. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan perdagangan manusia sebagai segala bentuk tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang dilakukan dengan cara kekerasan, ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Untuk memberikan perlindungan ini, Indonesia mengadopsi beberapa asas penting:
- Asas Keterpaduan: Perlindungan PMI harus mencerminkan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan.
- Asas Persamaan Hak: Calon PMI dan/atau PMI mendapatkan perlakuan, hak, dan kesempatan yang sama.
- Asas Pengakuan atas Martabat dan HAM: Perlindungan PMI harus menghormati harkat dan martabat manusia.
- Asas Anti-Perdagangan Manusia: Tidak adanya tindakan yang mengarah pada eksploitasi.
- Asas Berkelanjutan: Perlindungan PMI harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja.
Dalam konteks hukum dan ketatanegaraan, bekerja merupakan hak setiap individu dan warga negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan tingginya jumlah PMI yang ditempatkan di luar negeri. Sepanjang tahun 2024, tercatat 297.434 jiwa pekerja migran ditempatkan di berbagai negara (BP2MI, 2024). Tingginya angka ini membawa manfaat ekonomi, namun di sisi lain, juga meningkatkan risiko. Sepanjang tahun 2024, BP2MI telah menerima sebanyak 1.500 pengaduan dari PMI, dengan pengaduan terbanyak berasal dari Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Hong Kong, dan Kamboja. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Imigrasi, sebagai salah satu unsur dalam Satuan Tugas Pencegahan PMI Non-prosedural, memegang peranan penting. Pencegahan dini dilakukan melalui pengawasan dokumen paspor dan pemberangkatan di daerah embarkasi. Tujuannya adalah memastikan paspor tidak disalahgunakan untuk bekerja secara ilegal di negara tujuan.
Pemerintah juga mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non-Prosedural. Surat edaran ini menyoroti maraknya WNI di luar negeri yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain upaya di dalam negeri, perlindungan PMI juga bergantung pada implementasi hukum internasional. Setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri, sebuah konsep yang dikenal sebagai perlindungan diplomatik. Prinsip Exhaustion of Local Remedies dan Link of Nationality menjadi landasan dalam memberikan perlindungan ini. Untuk mendukung operasional perlindungan di luar negeri, Indonesia telah membentuk Citizen Service di 24 perwakilan RI di luar negeri.
Pekerja Migran Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara melalui remitansi, namun mereka sering kali menghadapi risiko serius seperti penipuan, penempatan ilegal, eksploitasi, dan perdagangan orang. Kasus yang diungkap di Batam menjadi bukti nyata betapa pentingnya penguatan sistem perlindungan. Perlindungan hukum bagi PMI tidak hanya bergantung pada peraturan domestik, tetapi juga membutuhkan ratifikasi perjanjian internasional. Selain itu, peran aktif masyarakat dan instansi seperti Imigrasi dalam pencegahan dini melalui pengawasan dokumen paspor dan pemberangkatan sangat krusial untuk meminimalkan risiko penempatan ilegal dan perdagangan orang. Pemahaman mendalam terhadap kasus-kasus semacam ini sangat penting sebagai dasar perumusan strategi perlindungan yang lebih efektif, penguatan penegakan hukum, dan edukasi masif bagi masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap PMI dapat bekerja dengan aman, bermartabat, dan hak-hak mereka terlindungi secara menyeluruh, baik di tanah air maupun di tanah rantau.