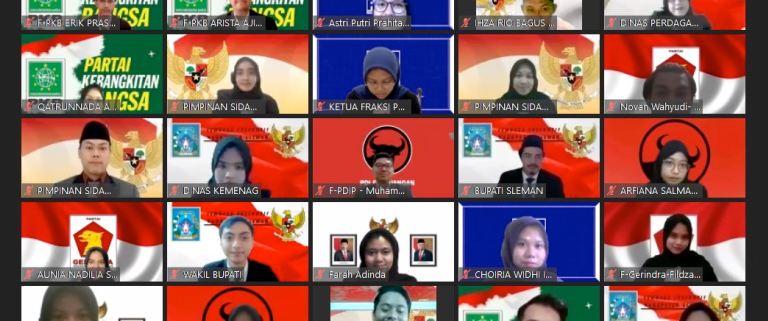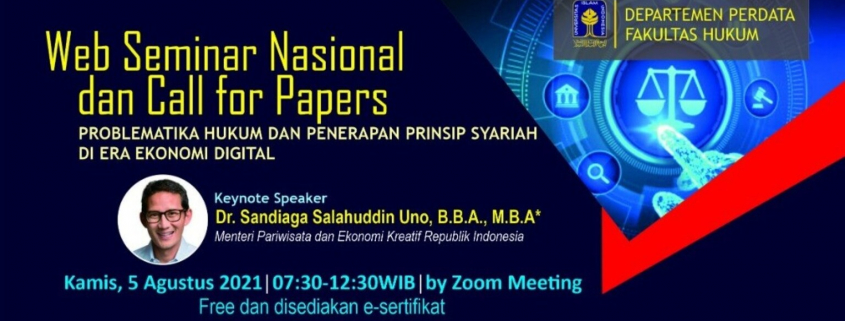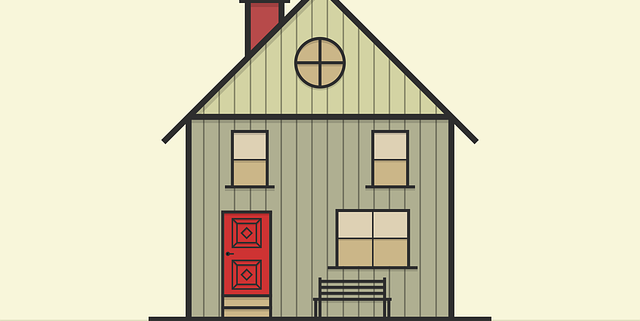Penulis: Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Departemen Hukum Tata Negara
Berakhirnya masa jabatan hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Mahkamah Agung mendorong mahkamah untuk segera mengajukan permohonan pengisian jabatan ke Komisi Yudisial.
Tampak kondisi saat ini akan menjadi sangat sulit bagi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengingat momen permohonan pengajuan hakim ad hoc yang tidak pas dengan tahun penganggaran Komisi Yudisial.
Di satu sisi, ada kesenjangan (gap) antara kebutuhan dan realisasi pengisian jabatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Di sisi lain, kekosongan kursi hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) yang akan purnatugas pada 22 Juli mendatang jelas akan mengganggu performa Mahkamah Agung.
Sampai sejauh ini, tiga opsi telah disediakan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung (Kompas, 14/7/2021). Pertama, perpanjangan masa jabatan hakim yang belum berusia 70 tahun tanpa seleksi ulang. Kedua, proses seleksi dilakukan pada tahun 2022. Ketiga, tahapan seleksi sudah mulai dilakukan tahun ini, tetapi pemenuhannya pada awal 2022.
Sampai dengan tulisan ini dibuat, opsi mengerucut pada pilihan ketiga (Kompas,5/7/2021). Artinya, Mahkamah Agung akan mengoptimalkan tiga hakim ad hoc yang ada, sambil menunggu terisinya dua kursi kosong yang diharapkan terpenugi pada awal tahun mendatang.
Berkaca dari kondisi di atas, setidaknya ada dua hal yang perlu diidentifikasi sebagai problem yang menengarai terjadinya krisis hakim di tubuh Mahkamah Agung.
Masa Jabatan
Saat ini pengaturan masa jabatan hakim ad hoc menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pembentuk undang-undang.
Belum jelas apa yang menjadi politik hukum pembedaan pengaturan masa jabatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan hakim agung. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung, masa jabatan hakim agung ditentukan berdasarkan usia maksimum 70 tahun. Sementara dalam Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hakim ad hoc memiliki masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
Dari aspek hukum positif, kita masih memiliki pekerjaan rumah cukup besar dalam menata jabatan hakim. Di level undang-undang, seharusnya pengaturan tentang jabatan hakim ad hoc perlu didetailkan lebih lanjut. Apakah syarat masa jabatan tertentu juga melekat pada hakim ad hoc di Mahkamah Agung?
Padahal, baik hakim agung maupun hakim ad hoc di Mahkamah Agung melewati proses dan tahapan seleksi yang sama, yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden.
Lebih dari itu, pembedaan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung juga menjadi tidak lagi begitu relevan mengingat baik hakim agung maupun hakim ad hoc di Mahkamah Agung memiliki beban kinerja dan tanggung jawab yang sama berdasarkan perintah undang-undang. Konsekuensi atas pembedaan masa jabatan itu mendorong Mahkamah Agung untuk mengajukan kebutuhan hakim ad hoc setiap lima tahun sekali. Dari sisi politik anggaran, kebutuhan di Mahkamah Agung tentu tidak selamanya dapat diikuti dengan ketersediaan anggaran di Komisi Yudisial. Kondisi inilah yang kerap menjadi titik problem yang justru mempersulit pemenuhan kebutuhan hakim di Mahkamah Agung.
Persetujuan DPR
Anasir lain yang menjadi problem pemenuhan kebutuhan hakim di Mahkamah Agung ialah keterlibatan DPR dalam memberikan persetujuan.
Pasal 24A Ayat (3) UUD menyebutkan bahwa “calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan sebagai hakim agung oleh Presiden”.
Jika dirunut berdasarkan original intent BAB IX Undang-Undang Dasar Negara (UUDN), kehadiran DPR sebenarnya tidak diperuntukkan melakukan supervise terhadap hasil kinerja Komisi Yudisial. Lagi-lagi pemahaman checks and balances ketatanegaraan kita tidak dapat dimaknai secara tekstual.
Hal ini karena berdasarkan sejarah perumusan Pasal 24A Ayat (3) UUDN, DPR bukanlah episentrum kekuasaan dalam menentukan proses seleksi calon hakim agung.
Ada prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang juga melekat pada pasal 24 Ayat (1) UUDN, yang seharusnya menutup ruang bagi partai politik untuk memilih dan menentukan calon hakim agung. Tujuan utamanya ialah mencegah terjadinya redundancy terhadap cara kerja yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial.
Intensi pelibatan DPR dalam konteks persetujuan sebenarnya tidak dalam kapasitas memilih dan menyeleksi ulang calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Sifat bersetujuan itu dalam kapasitas “right to confirm”, bukan dalam bentuk “right to select”.
DPR bisa menggunakan haknya dalam kondisi force majeure, missal proses seleksi yang menyalahi undang-undang, penetapan status tersangka, atau meninggal dunia.
Yang terjadi dalam praktik pascareformasi sebaliknya. Peran DPR kemudian bergeser sebagai lembaga penentu seleksi calon hakim agung dan cenderung mempersulit pemenuhan kebutuhan hakim di tubuh Mahkamah Agung.
RUU Jabatan Hakim
Merespons beberapa problema di atas, tidak ada salahnya untuk kembali membuka opsi penataan melalui RUU Jabatan Hakim. Baik itu menyangkut kedudukan, implikasi uang ditimbulkan dari pembedaan status jabatan hakim, hak dan kewajiban, maupun mendetailkan tata cara pengangkatan hingga pemberhentiannya.
Langkah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan guna mendorong pemenuhan kebutuhan hakim dan kinerja mahkamah yang independent dan akuntabel.
Tulisan ini sudah dimuat dalam rubrik Opini Kompas, 19 Juli 2021.