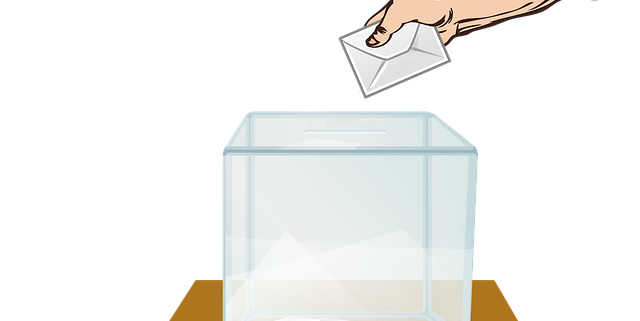Oleh:
Rendi Yudha Syahputra
Dosen FH UII
Penanganan kasus tewasnya dua orang yang diduga jambret akibat dikejar dan ditabrak oleh pengendara mobil, memantik kontroversi di seantero negeri. Legislatif disambut bak pahlawan kemenangan oleh rakyat, sedangkan aparat penegak hukum dicerca layaknya pecundang. Didepan sorot kamera, Legislatif tampil laksana hakim yang adil, tetapi tampak tidak berkenan mendengar penjelasan lengkap dari aparat penegak hukum. Apalagi melihat bukti-bukti yang dimiliki oleh aparat tersebut. Bahkan Legislatif juga tidak melibatkan keluarga atau pihak jambret, seakan kedua nyawa tersebut tidak berharga sama sekali di mata mereka. Kemudian Legislatif mengecam aparat penegak hukum (terutama polisi/ penyidik) yang dinilai hanya terpaku pada kepastian hukum (normatif prosedural) dan mengabaikan keadilan substantif.
Sebelum turut mencela aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tersebut, sebaiknya perlu diketahui bersama bahwa Legislatif merupakan pihak yang membuat dan menetapkan Prosedur Normatif bagi aparat penegak hukum dalam penanganan suatu kasus melalui undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Jadi, ketika penanganan suatu kasus sudah dilakukan sesuai dengan Prosedur Normatif, namun ternyata penanganan tersebut dirasakan tidak adil oleh rakyat, maka ada kemungkinan Prosedur Normatif yang ditetapkan Legislatif tidak disusun berdasarkan kebutuhan atau nilai-nilai yang diyakini rakyat. Itulah sebabnya, partisipasi rakyat (meaningful participation) dalam penyusunan undang-undang menjadi sesuatu yang sangat substansial.
Sistem Peradilan Pidana
Pada prinsipnya, prosedur penanganan suatu kasus (pidana) diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang didalamnya berisi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat dan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam sistem peradilan tersebut, Hakim merupakan pihak yang diberi kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu kasus (Pasal 1 angka 12 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP/ KUHAP 2025 atau Pasal 1 angka 8 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP/ KUHAP 1981). Sedangkan Penyidik merupakan pihak pencari dan pengumpul bukti, lalu Penuntut Umum merupakan pihak yang menentukan dapat tidaknya kasus dilimpahkan ke persidangan (Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 11 KUHAP 2025 atau Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 6 KUHAP 1981).
Bahkan dalam KUHAP 2025, pembagian peran aparat penegak hukum pada sistem peradilan tersebut semakin dipertajam dengan penegasan prinsip diferensiasi fungsional. Menurut Naskah Akademik RUU KUHAP yang diterbitkan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (Asperhupiki) pada bulan Januari 2025, keberadaan prinsip diferensiasi fungsional salah satunya dimaksudkan untuk meneguhkan posisi Penyidik sebagai pihak yang membantu tugas Penuntut Umum dalam penanganan suatu kasus, terutama dalam hal pengumpulan bukti (fakta). Jadi seandainya pada fase pertama Penyidik keliru dalam menerapkan hukum, Penuntut Umum yang notabene menjadi penanggungjawab utama dalam penanganan suatu kasus hukum, masih bisa mengkoreksi kekeliruan tersebut pada fase berikutnya.
Kemudian apabila diasumsikan bahwa keadilan substantif hanya dapat terwujud jika ditangani oleh orang dengan pemahaman hukum yang baik (anggaplah setidaknya berpendidikan hukum), maka penempatan Penyidik sebagai pihak yang hanya sebatas membantu tugas Penuntut Umum dalam penanganan suatu kasus adalah tepat. Karena seorang Penyidik memang tidak dituntut secara mutlak untuk berpendidikan hukum. Hal ini dapat dilihat dari kualifikasi akademis seorang Penyidik yang diatur dalam Pasal 2A ayat 1, Pasal 2C dan Pasal 3A ayat 1 PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP. Berbeda halnya dengan seorang Penuntut Umum yang dituntut secara mutlak untuk berpendidikan hukum (Pasal 9 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo Pasal 1 angka 10 KUHAP 2025 atau Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP 1981). Jadi dengan asumsi tersebut, dapat dikatakan bahwa disain utama seorang penyidik memang bukanlah untuk berbicara mengenai keadilan.
Prosedur Penanganan Kasus
Ketika Penyelidik/ Penyidik mendapatkan informasi awal tentang adanya suatu peristiwa dengan korban jiwa (misalnya ada dua orang pengendara sepeda motor yang tewas tergeletak bersimbah darah di jalan raya akibat benturan kendaraan), maka Penyelidik (dibawah koordinasi Penyidik) wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan untuk menentukan apakah peristiwa (hilangnya nyawa dua pengendara sepeda motor) tersebut merupakan Tindak Pidana atau bukan (Pasal 13 ayat 1 jo Pasal 20 ayat 1 jo Pasal 19 ayat 1 KUHAP 2025 atau Pasal 102 ayat 1 jo Pasal 105 KUHAP 1981).
Menurut ajaran dualistis hukum pidana, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana merupakan dua hal yang berbeda. Tindak Pidana hanya berbicara mengenai perbuatannya saja (cocok tidaknya peristiwa dengan rumusan pasal), sedangkan Pertanggungjawaban Pidana berbicara mengenai apakah orang yang memenuhi rumusan pasal tersebut patut dijatuhi hukuman pidana atau tidak. Apabila frasa “Tindak Pidana” dalam proses penyelidikan tersebut diartikan sebagai “Tindak Pidana” menurut ajaran dualistis, maka Penyelidik atau Penyidik cukup menilai perihal kecocokan antara peristiwa dengan rumusan pasal saja. Jadi, ketika Penyelidik atau Penyidik menilai bahwa peristiwa (hilangnya nyawa dua pengendara sepeda motor) cocok dengan rumusan suatu pasal (misal Pasal 311 ayat 5 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), maka selanjutnya Penyidik memang diwajibkan untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Penuntut Umum (Pasal 19 ayat 2 jo Pasal 58 KUHAP 2025 atau Pasal 106 KUHAP 1981 jo Pasal 109 ayat 1 KUHAP 1981).
Sama halnya dengan prosedur Penentuan Tersangka ataupun Penghentian Penyidikan. KUHAP 1981 maupun KUHAP 2025 hanya berbicara sebatas “Tindak Pidana”-nya saja dan sama sekali tidak menyinggung perihal Pertanggungjawaban Pidana atau Kesalahan pada kedua prosedur tersebut. Padahal Pertanggungjawaban Pidana berkaitan erat dengan alasan penghapus pidana seperti daya paksa (overmacht) dan pembelaan yang melampaui batas (noodweer exces). Ketika Prosedur Penentuan tersangka tidak mensyaratkan adanya Pertanggungjawaban Pidana, maka secara normatif memang Penyidik dapat menetapkan seseorang sebagai Tersangka manakala rumusan pasal Tindak Pidana yang disangkakan terpenuhi dan dapat dibuktikan secara memadai.
Uraian di atas baru membahas sebagian Prosedur Normatif yang terdapat dalam KUHAP dan belum seluruhnya. Namun dari sebagian itu saja, sudah terlihat bahwa Prosedur Normatif yang ada, berpotensi kembali mengusik “rasa keadilan” yang saat ini diyakini oleh rakyat. Sehingga pada momen seperti ini, seharusnya menjadi momentum introspeksi bagi Legislatif untuk mengevaluasi berbagai undang-undang yang pernah dibuat, terutama yang tidak mengakomodasi kemauan rakyat. Bukan malah dijadikan arena untuk mencari Kambing Hitam supaya terkesan bersih dari dosa-dosa (apalagi demi kontestasi 2029). Rakyat Indonesia yang cerdas, tahu siapa pecundang sesungguhnya.