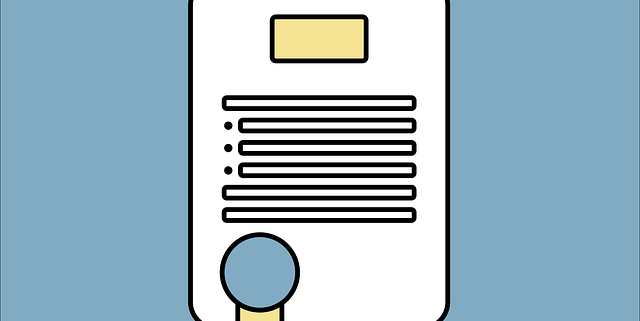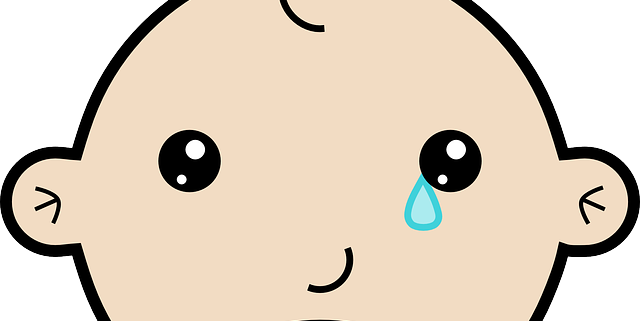Penulis: Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum UII, Departemen Hukum Perdata
Beberapa waku lalu Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan SIpil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengunggah video tentang “bagaimana membuat akta kelahiran” melalui channel YouTubenya. Salah satu materi yang menarik perhatian masyarakat adalah bahwa pasangan yang sudah menikah (secara agama) tapi tidak memiliki buku nikah dapat memiliki kartu keluarga (KK) dengan diberi tanda khusus. Tujuannya adalah memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan dari nikah siri. Disamping itu alasan lain adalah seorang anak mempunyai hak untuk tahu siapa ayahnya dan dituntut bertanggung jawab terhadap anaknya. Untuk itu Dukcapil akan mencatatkan dan menerbitkan KK bagi yang bersangkutan. Penerbitan KK ini tentunya disertai beberapa syarat-syarat seperti menunjukkan dokumen telah melakukan perkawinan secara agama (siri), melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), pernyataan dua (2) orang saksi dengan melampirkan identitas kependudukan.
Aktivitas pencatatan bagi nikah siri mendapatkan KK menjadi terobosan hukum baru yang difasilitasi oleh Dukcapil. Tentunya Dukcapil melakukan terobosan ini bukan tanpa sebab salah satunya mengikuti perintah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010. Putusan ini menggambarkan salah satu solusi bahwa anak dapat dihubungkan dengan orang tuanya bila perkawinan orang tuanya dapat dibuktikan kebenarannya (benar-benar menikah secara agama). Putusan ini jelas mengakui dan memberikan perlindungan hak terhadap anak yang dilahirkan karena nikah siri karena anak tidak boleh menjadi korban akibat perkawinan orang tuanya. Bahkan bila anak hasil nikah siri tidak diakui oleh ayahnya, tetapi bila dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan atau teknologi (Tes DNA) maka anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Tentunya pengakuan semacam ini tidak lahir dengan sendirinya, melainkan perlu penetapan dari pengadilan.
Disamping itu Dukcapil sebagai lembaga pencatat juga menjalankan perintah Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dimana tugas pokoknya adalah mencatatkan peristiwa penting penduduk Indonesia kedalam database kependudukan. Perkawinan dan kelahiran adalah contoh peristiwa penting yang diakui di Indonesia, sehingga harus dicatatkan kedalam database, tetapi implementasi pencatatan ini seyogyanya harus sejalan dengan syarat-syarat yang ada pula pada peraturan pelaksanaan tentang perkawinan. Persyaratan pemberian KK pada nikah siri memiliki essensi yang hampir sama dengan pencatatan perkawinan hanya saja pelaporanya dilakukan setelah nikah siri dan diberi tanda khusus bahwa itu belum tercatat.
Menilik beberapa alasan sejarah lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah semangat perlindungan hukum bagi kaum wanita dan anak-anak. Perlindungan dari kesewenangan oknum laki-laki ketika melakukan : perkawinan, perceraian, dan poligami sehingga lahirlah syarat-syarat (administrasi) yang cukup ketat untuk melakukannya. Kesemua syarat tertera jelas pada Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya, sehingga perkawinan yang memenuhi syarat maka para pihak akan mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Ada benang merah yang kuat mengapa syarat administrasi melakukan perkawinan itu ketat, karena ketika hendak bercerai pasangan ini akan melalui proses yang ketat juga. Indonesia adalah negara yang menganut asas “mempersulit perceraian” sehingga pasangan yang hendak bercerai harus mampu menunjukkan keinginan bercerai termasuk pembagian tanggung jawab terhadap anak. Patut diuji terobosan Dukcapil ketika pasangan nikah siri itu bercerai, apakah dapat dituntut secara hukum hak dan kewajiban si ayah meskipun telah menggunakan SPTJM.
Sebagai lembaga yang berwenang memberikan KK di Indonesia sebaiknya Dukcapil juga mengajak Kementerian Agama dan Pengadilan untuk selalu mensosialisasikan pentingnya penetapan perkawinan nikah siri (isbat nikah) kepada pelaku nikah siri. Sinergi yang positif diantara masing-masing lembaga seperti memfasilitasi memberikan akses kemudahan tempat, prosedur, biaya, waktu yang singkat hingga dilakukan secara terpusat pada salah satu lembaga dengan mekanisme yang mudah sehingga menarik minat pelaku nikah siri untuk menetapkan perkawinan. Hal ini justru lebih sejalan dengan semangat perlindungan hukum perkawinan, karena tidak hanya memperhatikan tanggung jawab anak, tetapi juga terhadap isteri.
Tulisan ini sudah dimuat dalam rubrik Analisis KR, Koran Kedaulatan Rakyat, 20 Oktober 2021.