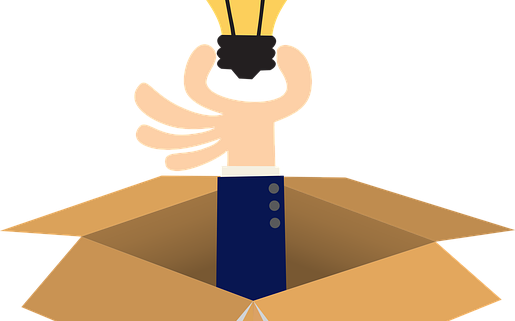“maka dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang ber-Iman (Ani-Nisa ayat 103)”
 Teknologi di era 4.0 sedang disosialisasi sedemikian rupa oleh pemerintah Repubik Indonesia untuk menjawab tantangan globalisasi yang selalu berkembang sangat cepat. Salah satu ciri sudah memasuki era 4.0 adalah pemanfaatan teknologi yang sudah menjadi alat penunjang atau sarana dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pemanfaatan teknologi ini dapat saja menjadi sebuah industri baru pada era ini. Satu dari beberapa ciri zaman di era teknologi 4.0 adalah adalah penggunaan aplikasi-aplikasi modern yang menjadi sarana untuk kemudahan hidup manusia. Aplikasi ini digunakan sebagai shortcut (jalur pintas) problem-problem atau masalah-masalah yang terjadi didalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah atau bahkan praktis.
Teknologi di era 4.0 sedang disosialisasi sedemikian rupa oleh pemerintah Repubik Indonesia untuk menjawab tantangan globalisasi yang selalu berkembang sangat cepat. Salah satu ciri sudah memasuki era 4.0 adalah pemanfaatan teknologi yang sudah menjadi alat penunjang atau sarana dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pemanfaatan teknologi ini dapat saja menjadi sebuah industri baru pada era ini. Satu dari beberapa ciri zaman di era teknologi 4.0 adalah adalah penggunaan aplikasi-aplikasi modern yang menjadi sarana untuk kemudahan hidup manusia. Aplikasi ini digunakan sebagai shortcut (jalur pintas) problem-problem atau masalah-masalah yang terjadi didalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah atau bahkan praktis.
Perkembangan ilmu falak di Indonesia saat ini seimbang dengan penggunaan sarana teknologi. Teknologi dapat menjadi alat bantu dalam menghitung, menentukan, bahkan mempermudah dalam melakukan ibadah shalat. Semakin berkembangnya teknologi tentunya dapat semakin menambah keakuratan dalam membantu perkembangan ilmu falak khususnya pada konteks penghitungan waktu shalat. Keakuratan tersebut tentunya harus ditunjang dengan data, dan kepastian lokasi titik bujur tempat, zona waktu dan lintang tempat sesuai daerah masing-masing tempat. Saat ini aplikasi tentang penerapan falak sudah banyak di buat di Indonesia, bahkan beriringan dengan kementerian agama pun turut mengeluarkan waktu-waktu yang tepat terkait awal pelaksanaan sholat.
Dalam penentuan waktu-waktu awal pelaksanaan sholat, pemerintah perlu kiranya memperhatikan lokasi-lokasi di tiap daerah secara rinci. Hal ini kembali kepada kepastian dari titik lokasi masing-masing masjid. Mengingat perbedaan titik lokasi saja sudah mampu menimbulkan perbedaan waktu awal sholat. Gambaran itu sudah tertuang pada sumber jadwal sholat berdasarkan sistem informasi manajemen bimas islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dasar penentuan waktu tersebut menggunakan rumus kordinat lokasi seperti : garis bujur (latitude), garis lintang (longtitude), ketinggian lokasi dari permukaan laut (height) dan zona waktu (Z). Untuk memudahkan penentuan waktu sholat yang berbeda-beda lokasi dimana perbedaan itu berbasis pada letak lokasi baik itu karena perbedaan bujur dan lintang, maka perlu kiranya penggunaan teknologi hadir sebagai solusi.
Beberapa teknologi aplikasi saat sudah mampu menunjukkan keberadaan dan awal waktu sholat yang tepat, tetapi apakah waktu-waktu tersebut sudah di tashih oleh lembaga yang berwenang ?, apabila sudah ditashih apakah waktu-waktu itu sudah akurat ? terkoneksi dari masing-masing zona tempatnya ? Untuk menjawab itu semua perlu sinergi peran antara lembaga terkait ilmu falak dan teknologi baik dari unsur perguruan tinggi dan pemerintah serta peran aktif masyarakat antara lain : (1) peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pengaturan jadwal sholat yang berbasis pada titik-titik lokasi masing-masing masjid. Hal ini diyakini bahwa titik-titik masjid pada tiap daerah itu mempunyai perbedaan waktu walaupun sedikit. (2) perguruan tinggi berperan untuk mengkaji dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa teknologi perlu digunakan walaupun itu berkaitan dengan ibadah. Pengkajian tentang peran teknologi informasi dalam ilmu falak perlu dijembatani oleh pendekatan-pendekatan ilmiah. Disamping itu perguruan tinggi merupakan rumah inovasi yang akan mendampingi pemerintah didalam menjawab problem keumatan. (3) melalui masyarakat perkembangan teknologi dan penerapan waktu sholat ini diimplementasikan. Masyarakat sebagai stakeholder dari teknologi serta pengguna kajian ilmu falak perlu mendapatkan benang merah manfaat dari teknologi. Jangan sampai dengan adanya teknologi dalam ibadah itu ditolak oleh masyarakat karena teknologi dianggap hal bid’ah, melainkan dengan adanya teknologi justru membawa pada masyarakat untuk rajib ibadah.
Umat islam di Indonesia harus dapat mengambil manfaat dari adanya perkembangan teknologi saat ini, khususnya digunakan untuk kepentingan yang dapat lebih mendekatkan diri pada sang pencipta Allah SWT. Dalam hal ini teknologi harus dirancang untuk dapat memudahkan umat islam dalam beribadah, mendekatkan diri pada Allah SWT, dan disebarkan untuk kemaslahatan dan manfaat bagi umat islam yang lain.
Kegiatan seminar nasional keislamaan dengan tema “mengembangkan ilmu falak berbasis pada teknologi di era 4.0 : peluang dan tantangannya ini sengaja dirancang untuk diselenggerakan oleh Universitas Islam Indonesia ,Kementerian Agama Kabupaten Sleman, dan Lembaga Teknindo dalam rangkat memberikan pengetahuan tentang peluang dan tantangan dalam hal perkembangan ilmu falak di era 4.0.
Pernah diterbitkan di Media Massa di Yogyakarta
Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H. Dosen Muda FH UII yang juga sedang studi lanjut Program Doktor UNAIR dan
Kepala Divisi Pengembangan DPPAI UII / Dosen Fakultas Hukum UII