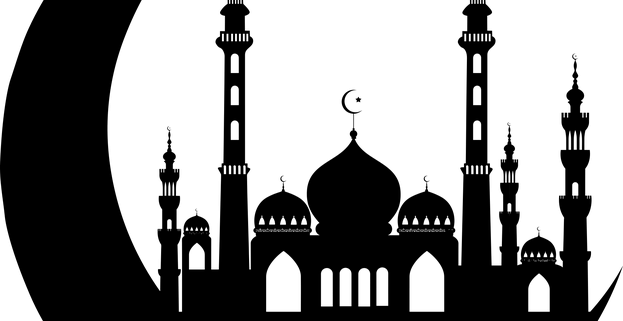Penulis: Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Departemen Hukum Tata Negara
Ketika sedang istirahat Jumat (27/4) kemarin sore handphone (HP) saya berdering-dering. Setelah saya tolak, berdering lagi dan berdering lagi. Ketika dengan agak malasmalasan saya mengangkat HP itu, ternyata peneleponnya adalah wartawati yang langsung saja nyerocos bertanya tentang Amien Rais dan langkahlangkah politiknya. “Mengapa Amien Rais sekarang ini bersikap frontal terhadap pemerintah?” tanya sang wartawati.
Saya jawab, sejauh yang saya kenal, sejak pertengahan 1980anposisiAmien Raismemangsepertiitu. Ia selalu mengambil posisi berhadapan dengan pemerintah. Ketika Presiden Soeharto masih sangat kuat, dia lawan Soeharto dan menjadi salah satu tokoh, bahkan ada yang menye but, lokomotif reformasi.
Saat Gus Dur berkuasa, dia hantam Gus Dur habis-habisan sampai makzul. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertakhta, Amien menyerang habis dan mengejek Pak SBY de ngan sebutan Pak Susi (comotan dari kata Susilo), bukan menyebut Presiden SBY seperti yang menjadi sebutan populer bagi sang presiden ketika itu. Saat ini pun dia melakukan gempuran yang bertubi-tubi terhadap Presiden Jokowi. Dalam ingatan dan catatan saya, entah kalau terlewat, Amien Rais itu hanya jinak ketika pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputeri berlangsung
Selama Presiden Megawati memerintah, Amien tidak melakukan serangan apapun. Pada saat itu, seingat saya, Amienhanya mengkritik perdana menteri negara jiran Mahathir Mohammad karena, katanya, berlaku tidak adil terhadap Anwar Ibrahim. Tapi dia terdiam ketika Mahathir balik menghardik mengatakan, “Jangan campuri urusan kami, urusitu ratusan ribu rakyat Indonesia yang menjadi pendatang haram dan mencari makan di Malaysia.” Waktu itu memang sedang hangat berita adanya 70.000 TKI yang dibuang di Nunukan oleh Pemerintah Malaysia.
Jadi bagi mereka yang kenal lama dengan Amien Rais, ya, begitu itulah dia sejak dulu.
“Apakah langkah-langkah yang seperti itu tidak merusak persatuan kita bangsa Indonesia?” tanya wartawati itu lagi.
“Tergantung orang yang memahaminya saja,” jawab saya.
Dalam iklim demokrasi, bagi Amien dan para pengikutnya, mungkin itu biasa saja sebagai bentuk kritik. Toh, Amien sendiri bisa dikritik juga. Saya, sebagai murid Pak Amien Rais, juga sering mengkritik. “Kritik seperti apa?” tanya sang wartawati lagi.
Ketika pekan lalu Amien Rais berbicara adanya partai Allah dan partaisetan, saya menyatakan bahwa dalam faktanya di Indonesia tidak tepat membuat kategori partai Allah dan partai setan. Di semua partaiituada juga orang-orang baik yang menjaga kejujurannya, tetapi juga di semua partai ada pencoleng dan koruptor terkutuknya. Coba kalau beranisebut satu saja partai mana yang partai setan? Atau sebut satu saja mana yang partai Allah?
Pasti tidak bisa karena di Indonesia sekarang memang tidak ada partai yang benarbenar buruk seperti kandang setan dan tidak ada partai yang benar-benar bersih seperti tempat bersemayamnya hambahamba Allah yang saleh.
Para pengikut Amien men coba meluruskan bahwa di dalarn Quran dan hadis ada istilah hizbullah dan hibuissyaithan seperti yang dikatakan Amien. Saya jawab, kalau itu, ya, me mang benar, tetapi kata hizb di dalam kedua sumber primer ajaran Islam itu bukan berarti partak seperti yang terkesan dinisbatkan Amien Rais terhadap keadaan Indonesia sekarang. Kata hibdi Quran dan hadis di situ berati barisan, tentara, kelompok, garda, pasukan
Ada Istilah hitbullah yang saat Nabi hidup dulu berarti barisan tentara Allah dan hixbusayaitan yang berarti kelompok pengikut setan. Ada juga istilah hizbul wahan yang berarti barisan pembelatanah air, barisan nasional, atau garda bangsa Saat ini memang ada kata hib yang dikaitkan dengan gerakan yang berbau politik seperti Hibullah di Lebanon atau Hizbut Tahrir. Tapi istilah partai Allah atau partai setan tidak bisa dipergunakan untuk memotret situasi politik, apalagi partai politik di Indonesia sekarang,
Jawaban mengada-adadile mukakan juga bahwa partat Allah itu adalah partai yang tidak membela penista agama. “Menurut saya klaim itu terlalu lancang. Bolehlah ada partal yang mengidaim tidak membe la penista agama, tetapi selama di partainya ada koruptor atau pembela koruptor, maka dia tidak boleh mengidaimpartainya sebagai partai Allah, Klaim se perti itu menodai kemahasuci an Allah karena koruptor dan para pembelanya itu justru dilaknat oleh Allah.
Selain soal partai Allah dan partai setan, wartawat itu bertanya juga tentang pernyataan Amien Rais bahwa khutbah di masjid boleh diisi dengan pesan politik. “Apakah itu berartanya wartawati itu. “Bisa benar dan bisa salah,” jawab saya. Bo leh saja di masjid kita me nyampaikan pesan politikasalkan yang politik tingkat tinggi Chrigh polities)tetapihindarkanlah menyampaikan pesan politik praktis (low politics) yang sudah menyangkut kepentingan praktis dari kelompok-kelompok politik yangada sekarang di Indonesia,
Dulu Nabi mengelola high Mies dari masjid, misalnya memerintahkantegaknya keadilan dan hukum, melakukan musya warah dalam mengelola peme rintahan, membantu kaum lemah, dan sebagainya. High po Nitics adalah politik sebagai kon sep dan inspirasi tentang ke baikan hidup bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Adapun low politics adalah politik praktis yang sudah diwarnai kepentingan kelompok-kelom pok politik yang saling bersaing seperti serigala
Saya setuju dengan Buya Syafii Maarif bahwa untuk konteks Indonesia yang seperti sekarang, di masjid hanya boleh me nyampaikan pesan politik ting kat tinggi (high politics) dan bu kan politik rendah (low politics) yang saling melakukan klaim atas kebenaran sebagai miliknya. Jadi pesan politik yang boleh disampaikan di masjid ada lahpesan yang sejuk yang tertuju kepada semuanya, bukan mendukung yang sebagian dan menyerang sebagian lainnya.
“Apakah sikap dan langkahLangkah Amien Rais itu tidak menimbulkan perpecahan di Partai Amanat Nasional (PAN) tanya wartawati itu lagi
“Jangan mancing maing. ya,” jawabsaya sambil tertawa.
PAN itu masih terlihat solid, masih menghormati Amien Rais, dan masih di bawah kendali Zulkifli Hasan. PAN tidak pecah, tetapi pengurus-pengurusnya dibuat sibuk oleh Amien Rais untuk menjelaskan bahwa banyak orang salah paham terhadap maksud baik Amien Rais. Pengurus PAN juga dibuat sibuk untuk menjelaslan bahwa pernyataan Amien Rais itu tidak ada kaitannya dengan PAN. Soal penjelasan pengurus PAN dipercaya atau pun tidak oleh masyarakat itu soal lain lagi.
Tulisan ini telah dimuat dalam koran SINDO, 28 April 2018.