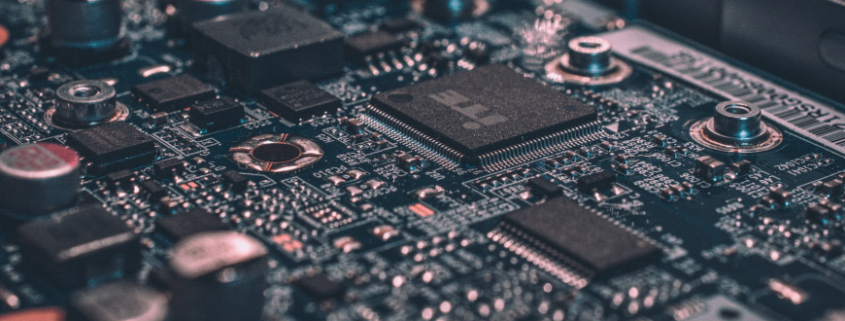Oleh: Budi Agus Riswandi [2]
Pendahuluan
Lahirnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah melahirkan harapan baru bagi para penulis buku terkait dengan manfaat hukum dan ekonomi yang akan diperoleh.[3] Adapun manfaat hukum, yakni berupa perlindungan hak cipta yang lebih efektif[4], sedangkan manfaat ekonomi berupa terbukanya peluang untuk mengeksploitasi nilai ekonomi yang ada di dalam ciptaan buku yang dilindungi hak cipta.[5]
Namun demikian, agar harapan penulis buku ini dapat diwujudkan, maka kehadiran UU No. 28 Tahun 2014 saja belum cukup, namun harus didukung dengan pemahaman dan kemampuan para penulis buku berkenaan dengan siklus tata kelola hak cipta (buku). Siklus tata kelola hak cipta (buku) sendiri kalau dilihat dari perspektif penulis bertumpu pada tiga aspek utama, yaitu; kreatifitas, eksklusifitas dan insentif.
Siklus Tata Kelola Hak Cipta Buku
Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[6], hak cipta sendiri merupakan hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud[7] (intangible assets). Oleh karena hak cipta dapat dimakna sebagai hak kebendaan yang sifatnya tidak berwujud, maka tidak mengherankan apabila hak cipta diperlukan untuk dikelola[8]. Dari sini tata kelola hak cipta menjadi sangat penting. Tata kelola hak cipta sendiri bertumpu pada tiga aspek, yakni kreativitas, eksklusivitas dan insentif atas karya. Ketiga aspek ini dalam hubungannya terjadi dalam bentuk siklus. Siklus tata kelola hak cipta dimulai dari kreativitas, eksklusivitas dan insentif atas karya.
Kreativitas karya adalah siklus pertama dalam tata kelola hak cipta. Kreativitas karya adalah suatu karya yang memiliki tingkat orisinalitas tertentu. Sebagaimana diketahui, orisinalitas terkait dengan benarkah si pencipta membuat karya tersebut.[9] Maka dalam konteks ini, menilai suatu karya itu orisinal atau tidak sangat tergantung dengan kebenaran dari para pencipta membuat karya tersebut. Ada dua kemungkinan dalam menetapkan suatu karya orisinal atau tidak. Pertama, jika para pencipta memiliki bukti yang kuat telah membuat karya, maka karya tersebut orisinal; dan Kedua, jika beberapa pencipta memiliki bukti kuat dan beberapa pencipta tidak memiliki bukti kuat, maka beberapa pencipta yang tidak memiliki bukti kuat karyanya akan dianggap tidak orisinal.
Dari pemahaman ini, maka untuk yang penetapan pertama, hal tersebut hanya akan berakibat kepada tinggi dan rendahnya kreativitas. Apabila perwujudannya beda sama sekali, maka karya tersebut akan dianggap tinggi kreativitas, tetapi apabila perwujudannya sama, maka karya tersebut akan dianggap rendah kreativitas. Sementara itu, apabila beberapa pencipta tidak memiliki bukti kuat, maka hal tersebut akan berakibat pada pelanggaran hak cipta atas suatu karya.
Siklus kedua dari tata kelola hak cipta yaitu eksklusivitas karya. Eksklusivitas karya adalah suatu karya diciptakan dan telah memenuhi persyaratan fiksasi, orisinalitas dan kreativitas dan terdapat di lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra, maka secara otomatically melahirkan hak cipta. Dengan lahirnya hak cipta, maka melahirkan hak eksklusif. Hak eksklusif ini memuat dua macam hak, yakni; hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mengambil manfaat ekonomi dari karya yang dilindungi hak cipta. Dalam hal penggunan hak cipta ini, maka tidak boleh pihak lain menggunakan hak cipta tersebut baik tanpa izin atau melawan hokum. Dari situasi ini, maka nilai eksklusivitas dari suatu karya dapat diwujudkan.
Sementara itu, insentif karya merupakan konsekuensi dari karya yang mengandung unsur kreativitas dan eksklusivitas. [10] Insentif sendiri dapat berupa nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini dapat diwujudkan dalam bentuk uang. Lazimnya, suatu karya yang dilindungi hak cipta dapat diambil insentifnya apabila dilakukan dengan cara dilisensikan atau diperjualbelikan.[11] Dari adanya kegiatan lisensi atau jual beli karya yang dilindungi hak cipta, maka akan menghasilkan nilai ekonomi berupa uang. Di sinilah letak dari insentif atas suatu karya yang mengandung unsure kreativitas dan eksklusivitas.
Setelah memahami siklus tata kelola hak cipta, maka karya buku-pun merupakan karya yang harus didekati dengan siklus tata kelola hak cipta.[12] Sebagaimana diketahui karya buku pada dasarnya memuat hak cipta. Oleh karena itu, buku tersebut harusnya dapat diperlakuan juga siklus tata kelola hak cipta. Siklus tata kelola hak cipta buku dapat mengacu kepada uraian di atas.
Implikasi Tata Kelola Hak Cipta (Buku)
Melihat pada siklus tata kelola hak cipta buku, maka tata kelola ini pada dasarnya sangat penting untuk menjamin keberlanjutkan atas munculnya karya-karya buku. Di samping itu, siklus tata kelola hak cipta buku jika diimplementasikan oleh para penulis buku dapat berimplikasi kepada moral, hokum, ekonomi dan sosial.
Siklus tata kelola hak cipta buku dapat berimplikasi pertama pada moral dapat dilihat dengan memperhatikan pentingnya membuat karya buku yang didasarkan pada nilai-nilai orisinalitas. Dengan memperhatikan nilai orisinalitas, maka karya buku yang dihasilkan dapat terhindar dari segi tindakan plagiarism. Tindakan plagiarism sendiri hakekatnya suatu perbuatan yang secara moral terlarang. Oleh karenanya, siklus tata kelola hak cipta buku pada akhirnya dapat berimplikasi pada moral dari penulis.
Implikasi kedua dari siklus tata kelola hak cipta buku berimplikasi pada hukum. Dengan diterapkannya siklus tata kelola hak cipta buku, — di mana salah satunya memperhatikan soal eksklusivitas karya, maka hal ini tentunya akan berdampak pada perlindungan hokum atas karya buku yang efektif. Bagaimanapun, eksklusivitas karya menegaskan kepada orang lain bahwa karya tersebut tidak boleh digunakan oleh pihak-pihak lain baik tanpa izin atau melawan hokum.
Implikasi ekonomi merupakan implikasi berikutnya dari siklus tata kelola hak cipta buku. Sebagaimana diketahui, buku merupakan karya yang dapat dieksploitasi secara ekonomi melalui penggandaan, pengumuman, dan pengadaptasian.[13] Dengan karya buku dieksploitasi secara ekonomi, maka manfaat ekonomi akan dapat dihasilkan oleh penulis. Manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dalam bentuk uang pada akhirnya diharapkan dapat mensejahterakan kondisi ekonomi dari penulis itu sendiri.
Implikasi yang lain dari siklus tata kelola hak cipta buku berupa implikasi sosial. Siklus tata kelola hak cipta buku apabila ditelusuri lebih jauh, hal ini juga akan berimplikasi pada hubungan antara penulis dan pihak-pihak terkait/ pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya hubungan yang baik antara penulis dengan pemangku kepentingan, maka secara sosial siklus tata kelola hak cipta buku telah menyuguhkan implikias sosial.
Kesimpulan
Siklus tata kelola hak cipta buku memuat aspek kreativitas, eksklusivitas dan insentif. Tiap aspek ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Apabila siklus tata kelola hak cipta buku diimplementasikan, maka aka nada proses berkelanjutan dari buku itu sendiri. Implikasi dari siklus tata kelola hak cipta buku berupa implikasi moral, hokum, ekonomi dan sosial.
Daftar Pustaka
Arthur R Miller dan Michael H Davis, Intellectual Property Patent, Trademarks, and copyright, St. Paul Minnesota: West Publishing Companym 1984.
David Brainbridge, Intellectual Property, England: Pitman Publishing, 1999.
M Hawin dan Budi Agus Riswandi, Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
Robert C. Megantz, How to License Technology, Singapore: John Wiley & Sons, INC, 1996.
Simon Stokes, Digital Copyright Law and Practice, London : Butterworths, 2002.
Yusron Isnaeni, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyberspace, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hk Cipta
[1] Disampaikan dalam Seminar Nasional dengan Tema Sistem Pemungutan Royalti di Bidang Literasi yang diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Hotel Tentrem, Selasa 27 Maret 2018.
[2] Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Ketua Umum Asosiasi Sentra Kekayaan Intelektual Indonesia (ASKII)
[3] Salah satu aturan hak cipta yang tertuang di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sifatnya memberikan harapan baru dalam bentuk harapan hokum dan ekonomi terkait dengan pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Di dalam UU No. 28 Tahun 2014, masalah LMK telah mendapatkan pengaturan secara detail dan lebih jelas daripada yang diatur di dalam UU No. 19 Tahun 2002.
[4] Aspek yang dilindungi dari hak cipta berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta berupa hak paternity dan integrity, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mengambil manfaatkan ekonomi dari ciptaan yang dilindungi hak cipta.
[5] David Bainbridge menyatakan:”Copyright provides a very useful and effective way of exploiting a works economically. It provides a mechanism for allocation of risks and income derived from the sale of the work. Lihat David Brainbridge, Intellectual Property, England: Pitman Publishing, 1999, hlm. 36.
[6] Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[7] Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[8] Pengelolaan hak cipta merupakan bagian yang tidak terpisah dari ilmu mengenai manajemen kekayaan intelektual.
[9] Arthur R Miller dan Michael H Davis menyatakan:”Originality does not imply novelty, it only implies that copyright claimant did not copy from someone else.” Lihat Arthur R Miller dan Michael H Davis, Intellectual Property Patent, Trademarks, and copyright, St. Paul Minnesota: West Publishing Companym 1984, hlm. 289.
[10] Gagasan ini merujuk pada teori perlindungan hak cipta yang dikenal dengan insentive theory. Menurut insentive theory bahwa perlindungan hak cipta merupakan insentif ekonomi yang diberikan kepada pencipta dalam rangka mendorong pencipta untuk dapat menginvestasikan waktu, usaha, keahlian dan segala sumber daya yang dimilikinya untuk proses membuat suatu kreativitas. Budi Agus Riswandi, “Catatan Pengaturan Manajemen Informasi Hak Cipta, Informasi elektronik Hak Cipta dan Sarana Kontrol Teknologi di dalam UU No. 28 Tahun 2014,” dalam M Hawin dan Budi Agus Riswandi, Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017, hlm. 125.
[11] Mengeksploitasi kekayaan intelektual secara ekonomi termasuk hak cipta dapat dilakukan dengan cara new venture, acquisition, joint venture, licesing, strategic alliance dan sale. Robert C. Megantz, How to License Technology, Singapore: John Wiley & Sons, INC, 1996, hlm. 1-3.
[12] Karya buku yang dilindungi oleh hak cipta pada dasarnya berupa ekspresi ide dari karya sastra, di mana dapat berupa karya ilmiah, puisi, gambar, legenda dan sebagainya. Karya sastra yang dituangkan ke dalam bentuk buku termasuk yang dilindungi hak cipta. Namun demikian, karya-karya lain yang dilindungi hak cipta tidak hanya berupa karya sastra, tetapi karya dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan termasuk dilindungi hak cipta juga. Di Inggris karya yang dilindungi hak cipta berdasarkan the Copyright, Designs and Patent Act 1988 (CDPA) terdiri dari: orginal literary works; original dramatic works; original artistic works; sound recordings, film, broadcasts and cable programmes; and the typographical arrangement of published edition. Lihat Simon Stokes, Digital Copyright Law and Practice, London : Butterworths, 2002, hlm. 24
[13] Mekanisme ini dikenal dengan eksploitasi hak-hak pencipta. Beberapa hak pencipta yang dapat ditarik keuntungan ekonominya berupa: hak reproduksi, hak adaptasi, hak distribusi, hak pertunjukan, hak penyiaran, hak program kabel, droit de suite, dan hak pinjam masyarakat. Lihat penjelasan lebih detail dalam Yusron Isnaeni, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyberspace, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 20-21.